Untuk semua laki-laki yang telah menyandang gelar Ayah,
“Kaulah Pahlawan bagi kami, anak-anakmu. Dan kami menyayangimu.”
*****
Hari itu adalah jadwal kepulangan bagi kami, santri yang berdomisili di Asrama. Semua menyambut dengan tingginya antusiasme. Tak terkecuali aku, pagi ini aku harus merapikan barang-barang yang akan aku bawa pulang. Pukul 9 pagi, kelas telah selesai dan mengijinkan bagi santri untuk pulang.
“Tak seperti biasanya, kami diijinkan pulang sebelum dzuhur”, pikirku dalam hati.
Namun, aku lebih memilih berdiam sementara sambil menunggu Ayahku datang menjemputku. Pikiranku terpelanting menuju sebuah objek yang kini tinggal jauh di sana. Ya, akhir-akhir ini aku sering terpikir akan objek itu. Dan berharap, saat kepulangan ini, aku dapat hadir di tempatnya. Beliaulah Kakekku. Satu-satunya Kakek yang aku temui hingga aku hampir berada di usia 17 tahun. Beliaulah yang mewariskan dan menguatkan aku untuk belajar di sebuah Lembaga Islam, Pondok Pesantren. Akulah satu-satunya cucu yang mengais ilmu di tempat semacam ini. Sekitar pukul 11, Ayahku telah datang untuk menjemputku pulang. Namun, aku ingin berjalan-jalan sebentar sebelum pulang untuk sedikit melepas penat. Ayahku pun setuju.
“Pak, HP-ku mana?, tanyaku.
Ayahku merogoh sak jaketnya dan memberikan benda mungil itu padaku.
“Ini.”, jawabnya.
Aku menyaut dan membukanya. Satu pesan diterima dan satu panggilan tak terjawab. Rupanya ada telepon dari Tanteku.
Aku sedikit bertanya-tanya, “Numben Tante telepon?”.
Lalu kubuka pesan, ternyata dari Ibu. De, mbah sedo tadi jam 11. Cepet pulang. Aku heran dan kaget bukan main. Bahkan sedikit merasa bagai orang ling-lung. Bingung. Tanpa pikir panjang, aku segera memberitahukan kepada Ayah.
“Pak, Ibu SMS. Katanya, Mbah sedo jam 11 tadi.”, ucapku dengan masih memasang wajah kebingungan.
“Innalillahi wa inna ilayhi roji’un. Padahal tadi Bapak tinggak nggak apa-apa loh!”, jawab Ayah.
Aku makin bingung, “Memangnya Mbah siapa sih?”, tanyaku.
“Mbah… ya, Mbahmu lah, De.”, jawab Ayah dengan nada yang sedikit tinggi.
Mataku pun terbelalak, kaget. Mungkin harapanku benar-benar akan terlaksana. Harapanku menemui beliau ditempatnya untuk terakhir kalinya. Bukan unuk melihat senyumnya atau mendengar wejangannya. Akhirnya, aku dan Ayahku pulang. Tak kurasa, airmata menitik membasahi pipi. Aku tiba di rumahku. Sedikit melepas lelah, makan siang dan menunaikan sholat Dzuhur. Semua memang tak pernah aku bayangkan, kehilangan seorang Kakek walaupun aku bukanlah cucu terdekat dengan beliau. Namun, kesedihan telah mengakar dalam hati meski aku belum melihat sosoknya untuk terakhir kali. Hingga, lamunan ini kembali menyerang jalan pikiranku. Tak ayal, buatku tak selera malahap makanan di hadapan mataku. Kenangan masa lalu yang kuingat adalah ketika aku dan Kakakku masih kecil. Kami bertamu ke rumah Kakek bersama Ayah dan Ibu. Ketika sampai di depan rumah, ternyata Kakek juga sedang ada tamu. Mungkin rekannya sewaktu masih dinas dulu. Dengan senyum, Kakek menyambut kami dan langsung menciumku dan Kakakku. Bahkan, mengenalkan pada tamunya yang duduk di kursi sampingnya.
“Iki putuku. Sing siji Cina, sing sijine Jepang. Haha…”, ucapnya sambil tertawa renyah.
Aku hanya mesam-mesem. Maklum, masih kecil belum tahu apa yang dimaksud Kakek. Ya, yang aku tahu kami berdua memang berkulit putih. Tak heran, Kakek menyebutnya dengan kata Cina dan Jepang. Dan………… pikiranku kembali pada saat ini. Siluet kenangan itu hilang bersama kembalinya sadarku. Kepiluan saat ditinggal orang terkasih memang tak bisa kupungkiri lagi. Tak berapa lama, aku berangkat menuju rumah duka. Ibu dan Kakakku beserta semua saudaraku telah lebih dulu ada di sana. Suasana duka telah kurasakan. Namun, aku tak melihatnya pada raut wajah Ayahku. Beliau tampak begitu tenang dan, mungkin, telah pasrah akan segalanya. Bahkan, pancaran sinar dari matanya masih bisa aku saksikan. Tiba aku di rumah duka. Aku coba tegarkan langkah melewati kerumunan orang yang melayat. Aku meninggalkan Ayahku yang sedang menyalami bapak-bapak yang hadir di situ. Aku langsung memasuki rumah dan aku dapati Ibuku, Tante, Om, Pakde, Bude serta saudara-saudara sepupuku. Mereka tak ada satupun yang tidak menangis. Aku tengok ke kananku. Kakek yang telah berbalut kafan putih dan siap untuk disholati. Aku terus berjalan membaur bersama handai taulan. Ada yang sempat bertanya,
“Mba Ade pulang kapan?”
“Pulangnya dijemput Bapak ya?”
“Bapak dimana?”
Beragam pertanyaan itu aku jawab dengan jawaban yang semestinya.
Lalu, aku langsung menuju tempat dimana Ibuku berdiri, menyalaminya, dan memeluknya. Rasa haru meyusup perlahan, hingga akupun kembali menangis. Aku melihat Kakakku tengah berdiri bersama seorang gadis, saudara sepupuku. Aku menghampiri keduanya.
“Pulang kapan, De?”, tanya Kakakku.
Aku menengok dan menjawab, “Barusan, habis dzuhur.”
Kakakku hanya mengangguk. “Eh, siapa sing menangi ninggale Mbah?”, tanyaku.
“Icha nih!”, jawab kakakku.
“Sempat mijetin malah.”, lanjutnya.
“Wahh!”, ucapku takjub.
Tiba-tiba, aku melihat wanita bercadar masuk dari pintu depan. Menyalamiku dan memelukku sambil menangis. Ya, dia saudara sepupuku juga. Kebetulan dia baru pulang mengajar, maka dia baru bisa hadir.
“Aku nggak dikabari.”, ucapnya sambil terus menangis.
Aku miris. Tapi, aku bersyukur masih bisa hadir di tempat ini. Karena, ada Om dan sepupuku yang tidak bisa hadir karena sedang berada di luar kota. Pasti mereka sedih sekali. Sekitar pukul setengah 4 sore, jenazah siap dimakamkan setelah disholati. Namun, sebelum berangkat ada sedikit acara atau sebut saja upacara pemberangkatan jenazah. Tak berapa lama, acara tersebut selesai dan siap mengantarkan jenazah ke TPU. Banyak mobil yang mengiringi mobil jenazah Kakek sampai ke pemakaman. Kemudian Lamunanku terpecah. Aku harus kembali menjemput sadarku. Aku menengok ke samping. Diyah, temanku di pesantren, kini duduk bersamaku. Tampaknya ia tahu aku sedang melamun tadi.
“Kenapa. De?”, tanyanya padaku.
Aku hanya menggeleng lemah dan kembali menatap buku bacaan yang sedang aku pegang.
“Aku cuma inget Mbahku aja. Beliau yang kasih motivasi biar aku betah di sini.”, ucapku sambil terus menerawang jauh ke depan.
Seolah aku melihat sebuah objek di sana. Diyah hanya tersenyum. “Mba Aniiiiiiiiiiiii”, teriak seorang dengan suara cemprengnya dan berlari menuju ke arah kami.
“Iiiiihhhhhhh……”, aku bersungut-sungut.
Aku paling tidak suka dipanggil Ani. Memang namaku Ade Irma Suryani. Tapi aku tidak suka bahkan tidak segan-segan aku mendamprat anak yang memanggilku dengan nama Ani. Terlalu feminin. Aku yang sejak kecil memang terlihat tomboy, belum bisa sepenuhnya berubah sikap layaknya perempuan sejati. Tapi tenang, aku normal. Buka pecinta sesama jenis. Ogah lahh yawww…… Anak itu mendekatiku. Dengan setengah terengah, dia mencoba mengatakan sesuatu padaku. Terlalu lama.
“Apa sih? Lari-lari nggak jelas!”, ucapku dengan sedikit cemberut.
“Nggak apa-apa, Mba. Tadi aku nyariin Mba, malah Mba di sini. Hehe..”, jawabnya sembari duduk di sampingku.
“Eh, kamu ngapain manggil aku ‘Mba Ani’? Aku sebel banget kalau dipanggil kayak gitu! Huhh…”, ucapku sambil buang muka.
Tiwi, anak yang tadi memanggilku, cemberut. Seperti merasa bersalah.
“Afwan ya, Mba. Aku spontan aja tadi. Mba itu emang pantesnya dipanggil Ani. Kalau dipanggil Ade kayak gimana gitu.”, jawabnya dengan penuh keseriusan sambil melambai-lambaikan tangannya layaknya rapper.
“Yayaya. Terserah kamu lah.. Cape’ deh!”, ucapku sembari berlalu dari tempat itu. Diyah dan Tiwi bertatapan. Mereka hanya mengedikan bahu kemudian berjalan mengikutiku.
*****
Aku berjalan menunduk. Kejadian beberapa bulan lalu membuatku sedikit down, dan tak jarang teman-teman menjumpaiku dalam keadan melayang ke dunia khayal. Yah, rasa sesal itu selalu ada. Belum ditambah dengan sedikit rasa minderku karena sebuah benda yang harus selalu aku pasang di depan mataku. Kacamata. Dengan minus yang kini makin menebal, aku merasa tak bisa hidup tanpa benda itu. Yah, dan memang akulah kini. Berbeda dengan keadaanku enam tahun yang lalu. Sebentar lagi aku akan menempuh Ulangan Umum Kenaikan Kelas XII. Aku akan berada di kelas XII beberapa bulan lagi. Aku harus serius. Tak boleh down dengan hal yang kini sering membuatku berkhayal.
“Aku kan harus kuat. Aku kan anak pahlawan nasional (dilihat dari nama aja udah ketahuan. Hehe…). Aku harus tunjukkin yang terbaik. Buat Bapak, buat Ibu. SEMANGAT!!!!”, ucapku dalam hati sambil mengepalkan tangan.
“Adeee…”, seseorang memanggilku.
Aku menoleh, melihatnya berjalan sedikit tergesa-gesa ke arahku.
“Sa atakalam ilayki.”, ucapnya. Aku sedikit bingung.
“Na’am.”, jawabku sembari mengikuti langkah Ayu, temanku yang tadi menghampiriku.
Kami terhenti di sebuah ruang yang tak jauh dari asrama. Remang-remang, karena tak ada lampu di sini.
“Ada sesuatu yang mau aku omongin ke kamu. ‘Afwan, tadi aku dapat kabar dari Ustadz, beliau bilang kalau…….”, Ayu berhenti bicara.
Aku makin penasaran. “Ayah kamu sakit. Masuk rumah sakit tadi pagi. Keadaannya masih biasa. Aku saranin kamu supaya pulang besok pagi. Tapi, lebih baik kamu hubungi rumah, Kakak atau Ibumu, mungkin.”, ucapnya lagi. Aku tersentak.
Merasa sendi-sendiku lepas dari engselnya. Lemas. “Ya, besok aku mau pulang. Malam ini aku mau hubungi Ibuku dulu.”, jawabku sambil berlalu dari tempat itu. Ketakutanku menguasai. Dan aku tak akan bisa tidur malam ini.
*****
Rumah Sakit Umum, pukul 13.00 WIB.
“Assalamu’alaykum.”, aku memasuki pintu kamar Wijayakusuma 4. Sesosok pria terbaring di atas kasur.
“Pulang kapan, De??”, tanya seseorang.
“Barusan. Langsung ke sini. Bapak sakit apa, Bu?”, tanyaku kemudian kudekati ranjang Ayahku.
Ku amati sosok yang kini sedang terlelap di depanku.
“Kata Dokter cuma kecapekan. Insya Allah besok udah bisa pulang.”, jawab Ibu sambil tersenyum.
Aku sedikit merasakan kelegaan di hati. Berarti paling tidak aku bisa kembali ke tanah rantauanku besok pagi.
“Alhamdulillah. Berarti besok aku bisa balik ke asrama.”, ucapku dengan datar.
Lagi, Ibuku hanya tersenyum. Senyum yang buatku sedikit bertanya-tanya. Malam ini aku menginap di Rumah Sakit bersama Kakak dan Ibuku. Kini, aku dapat melihat Ayahku tertawa. Bahkan, sedikit bercerita sesuatu padaku. Aku hanya miris. Merasakan keharuan atas apa yang kini terjadi pada Ayahku. Dan saat aku berada dalam henignya malam, tak kurasakan bahwa pipi ini basah bersama basahnya mukena yang kukenakan. Aku bersimpuh di hadap-Nya. Memuji asma-Nya dan meminta agar Ayahku selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin. Pagi tiba. Tak terasa semalam aku tertidur di atas sajadahku dan masih berbalut mukena. Kulirik jam tanganku. Pukul 4 pagi. Aku bergegas mandi dan sholat Shubuh. Tak lupa aku mendoakan untuk kesehatan keluargaku. Beberapa waktu kemudian, aku bersiap berangkat, kembali ke asrama. Aku akan diantar oleh Om Hanif, adik ipar Ayahku. Beliau telah siap. Aku berangkat setelah berpamitan pada Ayah dan Ibuku. Aku berjalan di belakang Om Hanif menuju tempat parkir. Kami memasuki mobil. Tak berapa lama, mobil telah meninggalkan pelataran parkir Rumah Sakit.
“Berarti kemarin kamu ijin, De??”, tanya Om Hanif yang tetap fokus pada kemudinya.
“Ya.”, jawabku singkat. Aku merasa aneh pagi ini.
“Kamu yang serius belajar di sana. Nggak usah mikir macem-macem. Pikiranmu itu di sana. Yang di rumah, insya Allah nggak apa-apa. Kamu kan pinter, De, jangan sampai ngecewain Bapak Ibu. Buat mereka bangga. Bentar lagi kenaikan kelas kan?? Yang rajin belajar yaa…”, ucap Om Hanif panjang lebar.
Ya, aku tak akan mau buat orang tuaku kecewa. Dan aku juga tak mau buat Om Hanif kecewa. Beliaulah yang menanggung semua kebutuhanku selama di Pesantren, mulai biaya sekolah, biaya hidup, dan lain sebagainya. Beliaulah ‘Pahlawan Keduaku’ setelah Ayah. Tak terasa, Toyota Vios milik Om Hanif memasuki pelataran Pondok Pesantren. Aku turun dan langsung berpamitan pada Om Hanif.
“Om langsung pulang ya. Harus cepet-cepet, ada perlu. Assalamu’alaykum.”, ucap Om Hanif sambil menutup kaca jendela mobil, dan segera memutar arah mobilnya.
Aku melihat mobil itu menghilang di tikungan, kemudian aku berjalan menuju asrama putri. Ada seseorang yang tampaknya memperhatikanku. Seorang laki-laki, seangkatan denganku. Tapi aku tak peduli dengan tatapannya. Aku berlalu tanpa melihat ke arahnya. Ia mendengus pelan. Bawalah pergi cintaku Ajak kemana engkau mau Jadikan temanmu… temanmu paling kau cinta Di sini ku pun begitu Mencintaimu di hidupku Di dalam hatiku…sampai waktu yang pertemukan kita nanti….. Lagu Bawalah Cintaku milik Afgan Syahreza, aku lantunkan. Serasa ada yang merasuk dalam hati. Entah. Hal itu terkadang aku rasakan. Wajar, usiaku hampir 17 tahun. Seseorang telah mengusik keheningan dan memecah lamunanku. Tapi, lupakan. Fokus pada studiku. Aku bersiap berangkat ke sekolah yang letaknya tak jauh dari asrama. Aku berjalan menikmati indahnya suasana di sekitarku. Aku merasakan kelegaanku.
“Ade Irma. Ade Irma, ke sini sebentar. Saya ada perlu sama kamu.”, ucap Ustadz Didi, pengampu pelajaran Matematika di Madrasah Aliyah.
“Ya.”, jawabku sambil berlari kecil memasuki kantor.
Aku mendekati Ustadz Didi, dan menunjuk sebuah kursi agar aku duduk di situ.
“Kamu darimana? Eh, maksud saya, kamu kemarin di asrama atau pulang?”, tanya beliau dengan tatapan selidik yang konyol.
Aku ingin tertawa melihatnya. Haha…
“Kemarin saya pulang. Nengok Bapak di Rumah Sakit.”, jawabku sambil tersenyum.
Beliau terdiam sejenak, “Ja.. Jangan bohong kamu!”,ucapnya dengan gagap nada tinggi.
Aku makin bingung. “Insya Allah, saya jawab dengan sejujurnya, Ustadz.”, jawabku tenang.
Ustadz Didi mengeryitkan dahinya, tampak bingung. Kini beliau menggaruk kepalanya yang, aku yakin, tidak gatal sama sekali.
“Saya jadi bingung. Tadi ada anak yang melaporkan sesuatu pada saya tentang kamu, tapi kamu tadi malam tidak di asrama. Aduh…”, ucapnya sambil geleng-geleng.
”Hah?? Melaporkanku?? Aku diam, Melaporkan apa, Ustadz??”, tanyaku penasaran dengan suasana hati makin tidak karuan.
Ustadz Didi ikut terdiam dan tiba-tiba bel berbunyi tanda jam masuk dan mulai pelajaran.
“Yah, sudah masuk. Saya nggak bisa jelaskan sekarang. Nanti saya bahas lagi, insya Allah. Sekarang kita masuk kelas dulu. Dan tolong bawakan LKS yang di atas meja sana.”, ucapnya sambil menenteng buku-bukunya dan menunjuk meja di sudut ruangan sana.
“Baik, Ustadz.”, jawabku dan segera berjalan mengambil LKS di atas meja sana.
Aku penasaran. Aku berjalan menuju kelas. Aku makin penasaran, heran dan aneh. Semua mata tertuju padaku. Semua terlihat mencibirku.
“Sok alim. Tapi nyatanya… Nggak banget deh!”, ucap seorang perempuan, adik kelasku di kelas XI.
Aku menatapnya dengan perasaan aneh, bingung dan sebagainya. Ada apa sebenarnya?? Apa kabar terakhir tentangku di sini?? Aku lalui pelajaran pertama dan kedua dengan buyarnya konsentrasiku. Benar-benar hilang fokusku. Apalagi setelah mendengar cerita dari Ustadz Didi barusan. Aku benar-benar tak tahu harus bagaimana. Seseorang telah mengatakan kabar palsu tentangku. Aku dituduh pergi dengan seorang lelaki tadi malam. Astaghfirullahal ‘adhiim. Aku hanya miris. Tangisku tak bisa kubendung.
“Udah lah, De. Aku tahu kamu nggak kayak gitu.”, ucap Diyah.
“Iya, De. Paling cuma kerjaan orang yang nggak suka sama kamu.”, ucap Mba Nia menimpali.
“Iya. Kan kemarin aku yang nyuruh kamu pulang.”, ucap Ayu.
Aku hanya bisa menangis. “Tega banget itu orang sama aku. Nggak tahu ya, kalau aku anak pahlawan?? Huhu…”, ucapku konyol sambil terus menangis.
Serentak teman-temanku tertawa. “Mba Ade loh! Sempet aja ngebanyol.”, kata Tiwi setengah tertawa.
“Udah lah, aku mau ke kelas aja.”, ucapku sambil menyeka airmata dan berjalan keluar kelas.
“Beneran??? Nggak malu kalau dilihat sama itu…….”, ucap Tiwi meledek.
Aku menoleh, memasang wajah bingung. “Sama siapa??”, tanyaku sambil berpikir.
”Sama itu tuh…. Sama yang kemarin dapet juara I. Haha….”, jawab Mba Nia dengan tawanya yang renyah.
“Iihh… ngayal banget! Nggak muluk-muluk deh! Nggak berharap juga. Tapi, kalau jodoh, aku nggak nolak. Hehe…”, ucapku terkekeh sambil berlari menjauhi mereka.
Teringat padanya. Mungkinkah aku jatuh cinta??? Atau hanya kagum padanya. “Please, De. Sinau sih ngapa!!!,”, ucapku dalam hati.
*****
Tiga hari kemudian. Padahal kemarin itu aku, bukan Ade. Kepentok udah ketahuan, aku kambing hitamin aja dia.
"Makanya nggak usak sok alim. Rasain sekarang dia dibenci sama semua orang. Hahahaha…”, ucap seorang perempuan diiringi dengan tawa teman-temannya.
Merasa sangat puas tampaknya. Tidak sengaja aku mendengarnya dari balik pintu kelas. Aku memasuki ruangan yang mereka tempati.
“Oh, jadi kamu toh. Dasar. Maunya apa kamu?? Pake segala laporin hal nggak penting kaya gitu. Kamu kalau iri sama aku nggak usah gitu caranya, Neng. Bagus apa??”, cerocosku tanpa pakai koma, apalagi titik.
“Kamu denger ya, De?”, tanyanya kebingungan.
Gelagapan. “Kalau aku nggak denger, aku nggak bakal bilang kaya gitu, Winda. Karepmu apa jane?? Aduh, keceplosan pake jawa. Maumu apa sebenernya?? Mau bikin namaku jelek di mata semua orang??? Selamat ya, kamu berhasil. Tapi aku bisa ngelakuin lebih dari itu. Ya nggak, Wi?? Ya nggak, Ay??”, ucapku dengan nada tinggi, tapi tak sampai tujuh oktaf, terlalu tinggi (ntar dikira lagi seriosa).
“Betul, betul, betul.”,jawab Tiwi dan Ayu. Winda tampak takut. Aku bisa melihat dari rautnya.
“Coba aja kalau bisa.”, tantangnya.
“Okeh. Emangnya aku takut sama kamu?? Cihh… orang kaya kamu mah tak tiup aja langsung mabur. Werrr… haha….”, kataku penuh percaya diri, lebih tepatnya angkuh.
Winda dan dua temannya berlalu dari tempat itu.
“Huuu…. Anak pahlawan dilawan, aku tembak pake senjata klenger loh!,” ucapku setengah teriak agar Winda mendengarnya. Tiwi dan Ayu tertawa dengan kerasnya.
“Okeh. Besok kalian temenin aku ke Ustadz Didi. Aku mau jelasin semuanya. Kalian jadi saksi mata buat kasus ini.”, ucapku layaknya detektif.
“Siap.”, jawab Tiwi dan Ayu bersamaan. Keesokan paginya.
“Jadi begitu ceritanya. Berarti sebenarnya yang tolol dia sendiri ya?? Sama aja kaya lapor tentang apa yang dia lakukan malam itu. Walah, bocah.”, ucap Ustadz Didi setelah mendengar apa yang aku ceritakan.
“Haha… katanya udah kepentok ketauhan sama Ustadz Sohib di depan gerbang. Jadinya saya yang jadi korban.”, jawabku dengan sedikit sinis.
Mengingat hal itu sangat membuatku geram. Gemas. Rasanya ingin menampar. “Ya, sudah. Kasus ini akan saya ajukan ke tingkat yang lebih tinggi supaya nanti bisa diselidiki lebih lanjut mengenai kebenarannya. Yang benar akan menang, insya Allah.”, ucapnya dengan nada yang bijaksana.
“Numben, biasanya agak gagap.”, kataku dalam hati.
Aku, Tiwi dan Ayu hanya tertawa kecil,
“Baik, Ustadz. Kami permisi dulu. Assalamu’alaykum.”, ucap Tiwi.
“Wa’alaykumussalam.”, jawab Ustadz Didi.
Kami beranjak dari tempat itu. Aku dan Ayu berjalan ke arah barat, menuju kelas kami, dan Tiwi berjalan ke kelasnya di sebelah timur. Sepanjang jalan aku dan Ayu bercakap-cakap tentang hal yang baru terjadi di kantor.
“Kok, numben Ustadz Didi nggak gagap ya?? Biasanya gagape poll! Ntu orang aslinya gagap apa nggak ya? Haha…”, ucapku ngelantur.
Ayu hanya senyum, menatap ke depan seolah menerawang sesuatu. Kemudian ia tertunduk bagai orang yang sedang menahan malu. Aku menoleh ke arahnya, bingung.
“Kamu denger nggak aku ngomong apa, Ay??”, tanyaku dengan datar.
Merasa diabaikan olehnya, aku sedikit muram.
“Eh. Hmm.. anu.. denger kok! Tapi kurang jelas. Bisa diulang?”, jawabnya serasa tanpa dosa.
Alamak. “Behh. Ogah ngulang! Nggak menayangkan siaran ulang!”, ucapku ketus sambil berjalan mendahuluinya.
Kini aku meninggalkannya di belakang.
“De… ‘Afwan. Tadi aku bener-bener lagi nggak konsen. Yah, mutung.”, ucap Ayu setengah bereriak.
Aku terus berjalan. Tanpa sengaja aku menabrak seseorang bertubuh jangkung. Aku terjatuh dan terpental beberapa sentimeter ke belakang. Aku mengaduh kesakitan. Kemudian aku mendongak,
“Kamu?”, ucapku takjub sembari menelan ludah.
Oh, tidak! Dia adalah virus yang selama ini mengganggu lamunanku.
“Kenapa? Kamu oke-oke aja kan? Nggak ada yang cedera kan?”, tanyanya dengan wajah kekhawatiran.
Aku melongo. Terpesona, mungkin.
“Hei. Hellow…”, katanya lagi sambil melambaikan tangannya di depan wajahku.
“Heh! Aku nggak apa-apa. Makasih udah bikin aku jatuh!”, ucapku ketus sembari bangkit dan berlalu meniggalkannya.
“Ketus amat. Hmm… tapi manis juga.”, ucap Diandar, orang yang menabrakku tadi, sambil tersenyum dan berjalan berlawanan arah denganku.
“Nightmare! Lupain! Lupain orang nggak penting itu! Lupain lupain!”, omelku yang kini mengundang perhatian teman-teman di kelasku.
“Apa sih, De?”, tanya Diyah yang tak lepas memandang LKS dihadapannya.
“Habis ditabrak orang nggak penting! Sampai jatuh pula! Iihhh…”, ucapku sambil menenggelamkan wajahku di antara kedua tanganku di atas meja.
“Siapa? Diandar?”, tanya Diyah padaku.
Aku terperangah, terkejut.
“Kok tahu?”, ucapku bingung. Diyah menoleh dan hanya tersenyum.
“Tadi malem kamu ngigau panggil-panggil Diandar.”, ucapnya santai.
Hah?? Aku tak percaya. “Apa iya? Jangan bohong kamu!”, ucapku dengan ekspresi tidak terima. Diyah mengada-ada pastinya.
“Wallahi.”, jawabnya singkat. Aku terdiam.
Mendengar kata itu aku tak bisa memungkiri bahkan mengelak. Diyah sudah bersungguh-sungguh atas nama Allah. Aku masih terdiam.
“Udah, belajar aja. Nanti ada ulangan Biologi loh!”, ucap Diyah.
Kacau! Aku baru ingat kalau nanti ada ulangan. Aku segera mengambil buku dan membukanya. Belajar Biologi. Satu minggu kemudian. Hasil ulangan Biologi diumumkan. Kali ini aku mendapat nilai tertinggi. Aku bahagia. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kelas. Semua mata tertuju pada sosok di luar sana. Ustadz Amir. Beliau masuk dan berbisik pada Ustadzah Ilma, pengampu Biologi di Madrasah Aliyah.
“Oh, iya. Silakan.”, ucap Ustadzah seolah memberi persetujuan.
“Ade Irma, ikut saya sebentar. Terimakasih, Ustadzah.”, ucap Ustadz Amir sambil berjalan keluar.
Aku bangkit dan mengikuti beliau keluar. Terheran-heran. Namun, aku tetap tenang mengikuti langkahnya. Aku sampai di kantor. Aku duduk di kursi coklat kayu di samping meja kecil di kantor itu.
“Ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kasus kamu dengan anak bernama Winda itu sudah selesai. Tadi malam dia datang ke rumah Ustadz Didi dan mengakui perbuatannya. Madrasah mengambil keputusan untuk mengembalikannya pada kedua orang tuanya….”, jelas Ustadz Amir.
“Ngikk? Drop Out maksudnya? Waduh..”, tanyaku dengan mata terbelalak.
“Iya, begitu kurang lebihnya. Dan kedua.. saya nggak mau basa-basi. Tadi kerabat kamu menghubungi kami, kamu disuruh pulang. Ada perlu di sana. Saya sarankan kamu pulang sekarang.”, ucapnya dengan nada ragu. Aku heran.
“Kenapa aku suruh pulang lagi?”, tanyaku dalam hati.
“Baiklah, Ustadz. Nanti saya ijin ke Wali Kamar.”, jawabku.
“Nggak perlu. Kami sudah ijinkan kamu ke Bidang Asrama.”, ucap Ustadz Amir,
“Kamu langsung pulang saja.”, lanjutnya. Aku keluar dari kantor setelah berpamitan.
Aku merasakan lemas yang luar biasa. Entahlah. Ada yang kurasa aneh dari perkataan Ustadz Amir tadi, seperti menyembunyikan sesuatu. *****
Aku tiba di rumahku. Sangat berbeda begitu aku memasuki jalan setapak menuju rumahku. Sangat ramai. Banyak sepeda motor berlalu lalang, keluar masuk halaman rumahku. Dan yang membuatku terkejut, bendera putih melambai-lambai di dekat pohon jambu di depan rumahku. Aku berlari sekencangnya menembus kerumunan orang-orang. Aku serasa hilang arah. Tiba aku di depan pintu rumah. Kulihat sesosok tubuh berbalut kafan putih kedua kalinya setelah wafatnya Kakekku dua bulan lalu. Kudekati sosok yang terbaring itu. Wajahnya pucat. Hidungnya tersumpal kapas. Aku mulai merasa airmata meleleh di pipiku.
“Bapaaaaakkkkk…….”, aku berteriak dan menangis sekerasnya.
Duniaku runtuh Jiwaku rapuh Ragaku meringkuk lesu Yaa Rabbiy.. Kaulah Sang Penggenggam Jiwa Lindungilah nyawa yang Kau hembuskan Lindungilah pula tiap nyawa yang Kau ambil kembali… Lindungilah Ayahku… Hatiku bersyair begitu. Memohon dan meminta perlindungan untuk Ayahku. Pandanganku buram. Remang-remang. Gelap. Aku mulai mencoba membuka mataku. Pening yang aku rasakan buatku enggan untuk bangkit.
“Pusing, De??”, tanya seseorang di sampingku, Kakakku.
Aku hanya mengangguk lemah sambil terus meringis kesakitan. Benar-benar pening.
“Kamu istirahat dulu. Mba tinggal bentar ya.”,ucap Kakakku sembari bangkit dan berlalu.
“Bapak dimana?”, tanyaku layaknya bocah kecil.
“Barusan dibawa ke pemakaman.”, jawab Kakakku singkat dan melanjutkan langkahnya keluar.
Aku lemas. Suasana duka masih aku rasakan. Seolah meruntuhkan dinding semangatku yang telah kubuat dari beberapa minggu yang lalu. Maklum, minggu depan akan berlangsung Ulangan Umum Kenaikan Kelas. Terkadang aku mengeluh. Aku kehilangan Ayahku saat aku ingin menunjukkan sesuatu yang hebat pada beliau. Ya, prestasiku saat kenaikan kelas XII, itulah yang ingin aku tunjukkan agar buat beliau bangga. Namun, harapan itu kandas. Aku harus segera kembali ke asrama. Aku tak mungkin berlama-lama di rumah. Dengan sedikit berat hati, aku berangkat.
“Hati-hati ya, Nduk. Sinau sing rajin. Ojo mikir macem-macem. Gawe bapak seneng neng kono.”, ucap Ibuku sambil menangis memelukku.
“Iya, Bu. Doain nilaiku apik.”, jawabku sembari melepas pelukan Ibuku.
“Assalamu’alaykum.”, ucapku lagi sambil berjalan keluar rumah.
“Wa’alaykumussalam.”, jawab Ibu dan Kakakku bersamaan.
Aku berangkat dengan bis umum. Sepanjang perjalanan, aku lebih banyak diam. Memandang keluar melalui jendela bis. Terbayang siluet memori bersama Ayahku. Banyak sekali kenangan indah bersama beliau. Terlalu jauh aku mengkhayal, hingga tak terasa seseorang sedang mengamatiku.
“Permisi.”, ucapnya. Aku sedikit terlonjak kaget.
“Kamu? Kok bisa di sini??”, tanyaku padanya.
Orang itu lagi! “Ya, niatnya aku mau ke rumah kamu. Mewakili kelas untuk ta’ziyah. Malah kamu udah mau balik ke Pondok. Ya udah, akhirnya aku ngikutin kamu.”, jelasnya sambil tersenyum lebar. Manis.
“Oo… tapi kenapa harus kamu?”, tanyaku heran.
Dia justru tertawa lebar mendengar pertanyaanku. Orang aneh, pikirku.
“Aku kan ketua kelas.”, jawabnya singkat.
Dengan sedikit malu, aku mengalihkan pandanganku keluar jendela. Setelah itu, kami terdiam sampai ke tempat tujuan.
*****
Sebulan kemudian. Hari ini adalah pembagian hasil Ulangan Umum Kenaikan Kelas. Aku pasrah.
“Situ lah, nilaiku mau berapa. Kemarin aku ngerjainnya nggak niat. Nggak semangat. Ketambahan ada virus. Bah, aku ngerasa bego banget gara-gara itu orang!”, omelku didepan cermin, bersiap-siap akan berangkat ke sekolah, mengambil buku Raport.
“Emang gara-gara siapa? Hayooo….”, ledek Ana, teman sekamarku. “Oh.. anu.. itu lah. Orang nggak penting.”, jawabku gelagapan. Bahaya kalau dia tahu. Aku berjalan menuju kelas untuk mengambil Raport. Tiba-tiba ada teman-temanku, yang berjalan dari arah kelas, menyalami sambil tersenyum padaku.
“Selamat, De. Dapet ranking I nih! Semangat terus ya!”, ucap Ima. Aku bingung.
“Apa sih? Emang ranking I ya?”, tanyaku dengan nada blo’on.
Semua teman-temanku tertawa lepas melihat kebodohanku. Aku yang tidak percaya, langsung berlari kencang menuju kelas. Tiba di depan kelas, aku berhenti sejenak. Kemudian, aku berjalan perlahan memasuki kelas.
“Ade Irma. Silakan, ini buku Raportmu. Selamat, terus tingkatkan prestasimu.”, ucap Ustadzah Zakiyah, wali kelasku.
Aku makin tidak percaya. Aku buka lembar-lembar Buku Hijau itu. Tertulis angka ‘I’ di kolom peringkat.
“Hah??? Aku… ranking I?? Ya syok! Haha……….”, ucapku sambil tertawa bahagia.
“Alhamdulilah… Bapak, aku ranking I. Semoga Bapak seneng tahu prestasiku di sana.”, ucapku dalam hati.
Aku berlari keluar kelas, menghampiri teman-temanku sambil melompat-lompat kegirangan. Teman-temanku hanya tertawa melihat tingkahku.
“Ani.”, panggil seseorang di belakangku.
Aku bersungut-sungut.
“Jangan panggil……….. kamu lagi???”, ucapku kaget.
Akupun melongo. Terpesona untuk kesekian kalinya. Senyumanmu buat aku deg-degan Tatapanmu buatku jadi deg-degan Diandar.
“Selamat ya… Jangan pernah menyerah hanya karena kamu kehilangan orang yang kamu sayangi. Bentar lagi kita kan kelas XII, harus makin rajin. Berjuang sama-sama yaa….”, katanya sambil tersenyum manis.
Lagi, aku melayang. Mungkinkah ada rasa???
“Iya. Makasih banyak, Andar.”, ucapku sedikit kikuk.
Diandar berlalu, namun menoleh dan tersenyum lagi.
“Kalau lulus, ngajar di sini aja. Kamu bakal ketemu sama aku.”, ucapnya lagi kemudian pergi dengan senyum manisnya.
Dan harus kusadari. Aku mengaguminya. Dan akupun harus menyadari, kehilangan seseorang yang aku sayangi tak semestinya membuatku terjatuh dan lemah. Walaupun seseorang itu takkan abadi, tapi aku yakin kegigihannya dalam menjalani hidupnya yang harus aku teladani.
“Bapak, semangatmu abadi dalam jiwaku. Aku akan buatmu bangga walau kau tak bisa melihatku dalam dunia nyata. Kau dalam keabadian di sisi-Nya.”, bisikku dalam hati.
Tuhan tolonglah Sampaikan sejuta sayangku untuknya Ku trus berjanji takkan khianati pintanya Ayah dengarlah Betapa sesungguhnya ku mencintaimu Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu Aku menatap Diandar yang kini berada di ujung jalan sana. Dia menoleh ke arahku, dan melambaikan tangannya padaku. Aku hanya tersenyum.
“Ciyeehhhh….. jadi dia orang yang nggak penting itu??”, tanya Ayu dengan nada meledek.
“Sekarang dia penting buat aku.”, jawabku, namun hanya dalam hati.
Itu sudah, tahun depan aku akan menghadapi sesuatu yang lebih istimewa, Ujian Nasional. Aku harus lebih semangat lagi.
“Bapak, doakan aku.”, bisikku lagi.
Semua belum berakhir. Masih perlu ada perjuangan untuk meraih yang aku inginkan.
*****
(Karya Kusmaningsih)
“Kaulah Pahlawan bagi kami, anak-anakmu. Dan kami menyayangimu.”
*****
Hari itu adalah jadwal kepulangan bagi kami, santri yang berdomisili di Asrama. Semua menyambut dengan tingginya antusiasme. Tak terkecuali aku, pagi ini aku harus merapikan barang-barang yang akan aku bawa pulang. Pukul 9 pagi, kelas telah selesai dan mengijinkan bagi santri untuk pulang.
“Tak seperti biasanya, kami diijinkan pulang sebelum dzuhur”, pikirku dalam hati.
Namun, aku lebih memilih berdiam sementara sambil menunggu Ayahku datang menjemputku. Pikiranku terpelanting menuju sebuah objek yang kini tinggal jauh di sana. Ya, akhir-akhir ini aku sering terpikir akan objek itu. Dan berharap, saat kepulangan ini, aku dapat hadir di tempatnya. Beliaulah Kakekku. Satu-satunya Kakek yang aku temui hingga aku hampir berada di usia 17 tahun. Beliaulah yang mewariskan dan menguatkan aku untuk belajar di sebuah Lembaga Islam, Pondok Pesantren. Akulah satu-satunya cucu yang mengais ilmu di tempat semacam ini. Sekitar pukul 11, Ayahku telah datang untuk menjemputku pulang. Namun, aku ingin berjalan-jalan sebentar sebelum pulang untuk sedikit melepas penat. Ayahku pun setuju.
“Pak, HP-ku mana?, tanyaku.
Ayahku merogoh sak jaketnya dan memberikan benda mungil itu padaku.
“Ini.”, jawabnya.
Aku menyaut dan membukanya. Satu pesan diterima dan satu panggilan tak terjawab. Rupanya ada telepon dari Tanteku.
Aku sedikit bertanya-tanya, “Numben Tante telepon?”.
Lalu kubuka pesan, ternyata dari Ibu. De, mbah sedo tadi jam 11. Cepet pulang. Aku heran dan kaget bukan main. Bahkan sedikit merasa bagai orang ling-lung. Bingung. Tanpa pikir panjang, aku segera memberitahukan kepada Ayah.
“Pak, Ibu SMS. Katanya, Mbah sedo jam 11 tadi.”, ucapku dengan masih memasang wajah kebingungan.
“Innalillahi wa inna ilayhi roji’un. Padahal tadi Bapak tinggak nggak apa-apa loh!”, jawab Ayah.
Aku makin bingung, “Memangnya Mbah siapa sih?”, tanyaku.
“Mbah… ya, Mbahmu lah, De.”, jawab Ayah dengan nada yang sedikit tinggi.
Mataku pun terbelalak, kaget. Mungkin harapanku benar-benar akan terlaksana. Harapanku menemui beliau ditempatnya untuk terakhir kalinya. Bukan unuk melihat senyumnya atau mendengar wejangannya. Akhirnya, aku dan Ayahku pulang. Tak kurasa, airmata menitik membasahi pipi. Aku tiba di rumahku. Sedikit melepas lelah, makan siang dan menunaikan sholat Dzuhur. Semua memang tak pernah aku bayangkan, kehilangan seorang Kakek walaupun aku bukanlah cucu terdekat dengan beliau. Namun, kesedihan telah mengakar dalam hati meski aku belum melihat sosoknya untuk terakhir kali. Hingga, lamunan ini kembali menyerang jalan pikiranku. Tak ayal, buatku tak selera malahap makanan di hadapan mataku. Kenangan masa lalu yang kuingat adalah ketika aku dan Kakakku masih kecil. Kami bertamu ke rumah Kakek bersama Ayah dan Ibu. Ketika sampai di depan rumah, ternyata Kakek juga sedang ada tamu. Mungkin rekannya sewaktu masih dinas dulu. Dengan senyum, Kakek menyambut kami dan langsung menciumku dan Kakakku. Bahkan, mengenalkan pada tamunya yang duduk di kursi sampingnya.
“Iki putuku. Sing siji Cina, sing sijine Jepang. Haha…”, ucapnya sambil tertawa renyah.
Aku hanya mesam-mesem. Maklum, masih kecil belum tahu apa yang dimaksud Kakek. Ya, yang aku tahu kami berdua memang berkulit putih. Tak heran, Kakek menyebutnya dengan kata Cina dan Jepang. Dan………… pikiranku kembali pada saat ini. Siluet kenangan itu hilang bersama kembalinya sadarku. Kepiluan saat ditinggal orang terkasih memang tak bisa kupungkiri lagi. Tak berapa lama, aku berangkat menuju rumah duka. Ibu dan Kakakku beserta semua saudaraku telah lebih dulu ada di sana. Suasana duka telah kurasakan. Namun, aku tak melihatnya pada raut wajah Ayahku. Beliau tampak begitu tenang dan, mungkin, telah pasrah akan segalanya. Bahkan, pancaran sinar dari matanya masih bisa aku saksikan. Tiba aku di rumah duka. Aku coba tegarkan langkah melewati kerumunan orang yang melayat. Aku meninggalkan Ayahku yang sedang menyalami bapak-bapak yang hadir di situ. Aku langsung memasuki rumah dan aku dapati Ibuku, Tante, Om, Pakde, Bude serta saudara-saudara sepupuku. Mereka tak ada satupun yang tidak menangis. Aku tengok ke kananku. Kakek yang telah berbalut kafan putih dan siap untuk disholati. Aku terus berjalan membaur bersama handai taulan. Ada yang sempat bertanya,
“Mba Ade pulang kapan?”
“Pulangnya dijemput Bapak ya?”
“Bapak dimana?”
Beragam pertanyaan itu aku jawab dengan jawaban yang semestinya.
Lalu, aku langsung menuju tempat dimana Ibuku berdiri, menyalaminya, dan memeluknya. Rasa haru meyusup perlahan, hingga akupun kembali menangis. Aku melihat Kakakku tengah berdiri bersama seorang gadis, saudara sepupuku. Aku menghampiri keduanya.
“Pulang kapan, De?”, tanya Kakakku.
Aku menengok dan menjawab, “Barusan, habis dzuhur.”
Kakakku hanya mengangguk. “Eh, siapa sing menangi ninggale Mbah?”, tanyaku.
“Icha nih!”, jawab kakakku.
“Sempat mijetin malah.”, lanjutnya.
“Wahh!”, ucapku takjub.
Tiba-tiba, aku melihat wanita bercadar masuk dari pintu depan. Menyalamiku dan memelukku sambil menangis. Ya, dia saudara sepupuku juga. Kebetulan dia baru pulang mengajar, maka dia baru bisa hadir.
“Aku nggak dikabari.”, ucapnya sambil terus menangis.
Aku miris. Tapi, aku bersyukur masih bisa hadir di tempat ini. Karena, ada Om dan sepupuku yang tidak bisa hadir karena sedang berada di luar kota. Pasti mereka sedih sekali. Sekitar pukul setengah 4 sore, jenazah siap dimakamkan setelah disholati. Namun, sebelum berangkat ada sedikit acara atau sebut saja upacara pemberangkatan jenazah. Tak berapa lama, acara tersebut selesai dan siap mengantarkan jenazah ke TPU. Banyak mobil yang mengiringi mobil jenazah Kakek sampai ke pemakaman. Kemudian Lamunanku terpecah. Aku harus kembali menjemput sadarku. Aku menengok ke samping. Diyah, temanku di pesantren, kini duduk bersamaku. Tampaknya ia tahu aku sedang melamun tadi.
“Kenapa. De?”, tanyanya padaku.
Aku hanya menggeleng lemah dan kembali menatap buku bacaan yang sedang aku pegang.
“Aku cuma inget Mbahku aja. Beliau yang kasih motivasi biar aku betah di sini.”, ucapku sambil terus menerawang jauh ke depan.
Seolah aku melihat sebuah objek di sana. Diyah hanya tersenyum. “Mba Aniiiiiiiiiiiii”, teriak seorang dengan suara cemprengnya dan berlari menuju ke arah kami.
“Iiiiihhhhhhh……”, aku bersungut-sungut.
Aku paling tidak suka dipanggil Ani. Memang namaku Ade Irma Suryani. Tapi aku tidak suka bahkan tidak segan-segan aku mendamprat anak yang memanggilku dengan nama Ani. Terlalu feminin. Aku yang sejak kecil memang terlihat tomboy, belum bisa sepenuhnya berubah sikap layaknya perempuan sejati. Tapi tenang, aku normal. Buka pecinta sesama jenis. Ogah lahh yawww…… Anak itu mendekatiku. Dengan setengah terengah, dia mencoba mengatakan sesuatu padaku. Terlalu lama.
“Apa sih? Lari-lari nggak jelas!”, ucapku dengan sedikit cemberut.
“Nggak apa-apa, Mba. Tadi aku nyariin Mba, malah Mba di sini. Hehe..”, jawabnya sembari duduk di sampingku.
“Eh, kamu ngapain manggil aku ‘Mba Ani’? Aku sebel banget kalau dipanggil kayak gitu! Huhh…”, ucapku sambil buang muka.
Tiwi, anak yang tadi memanggilku, cemberut. Seperti merasa bersalah.
“Afwan ya, Mba. Aku spontan aja tadi. Mba itu emang pantesnya dipanggil Ani. Kalau dipanggil Ade kayak gimana gitu.”, jawabnya dengan penuh keseriusan sambil melambai-lambaikan tangannya layaknya rapper.
“Yayaya. Terserah kamu lah.. Cape’ deh!”, ucapku sembari berlalu dari tempat itu. Diyah dan Tiwi bertatapan. Mereka hanya mengedikan bahu kemudian berjalan mengikutiku.
*****
Aku berjalan menunduk. Kejadian beberapa bulan lalu membuatku sedikit down, dan tak jarang teman-teman menjumpaiku dalam keadan melayang ke dunia khayal. Yah, rasa sesal itu selalu ada. Belum ditambah dengan sedikit rasa minderku karena sebuah benda yang harus selalu aku pasang di depan mataku. Kacamata. Dengan minus yang kini makin menebal, aku merasa tak bisa hidup tanpa benda itu. Yah, dan memang akulah kini. Berbeda dengan keadaanku enam tahun yang lalu. Sebentar lagi aku akan menempuh Ulangan Umum Kenaikan Kelas XII. Aku akan berada di kelas XII beberapa bulan lagi. Aku harus serius. Tak boleh down dengan hal yang kini sering membuatku berkhayal.
“Aku kan harus kuat. Aku kan anak pahlawan nasional (dilihat dari nama aja udah ketahuan. Hehe…). Aku harus tunjukkin yang terbaik. Buat Bapak, buat Ibu. SEMANGAT!!!!”, ucapku dalam hati sambil mengepalkan tangan.
“Adeee…”, seseorang memanggilku.
Aku menoleh, melihatnya berjalan sedikit tergesa-gesa ke arahku.
“Sa atakalam ilayki.”, ucapnya. Aku sedikit bingung.
“Na’am.”, jawabku sembari mengikuti langkah Ayu, temanku yang tadi menghampiriku.
Kami terhenti di sebuah ruang yang tak jauh dari asrama. Remang-remang, karena tak ada lampu di sini.
“Ada sesuatu yang mau aku omongin ke kamu. ‘Afwan, tadi aku dapat kabar dari Ustadz, beliau bilang kalau…….”, Ayu berhenti bicara.
Aku makin penasaran. “Ayah kamu sakit. Masuk rumah sakit tadi pagi. Keadaannya masih biasa. Aku saranin kamu supaya pulang besok pagi. Tapi, lebih baik kamu hubungi rumah, Kakak atau Ibumu, mungkin.”, ucapnya lagi. Aku tersentak.
Merasa sendi-sendiku lepas dari engselnya. Lemas. “Ya, besok aku mau pulang. Malam ini aku mau hubungi Ibuku dulu.”, jawabku sambil berlalu dari tempat itu. Ketakutanku menguasai. Dan aku tak akan bisa tidur malam ini.
*****
Rumah Sakit Umum, pukul 13.00 WIB.
“Assalamu’alaykum.”, aku memasuki pintu kamar Wijayakusuma 4. Sesosok pria terbaring di atas kasur.
“Pulang kapan, De??”, tanya seseorang.
“Barusan. Langsung ke sini. Bapak sakit apa, Bu?”, tanyaku kemudian kudekati ranjang Ayahku.
Ku amati sosok yang kini sedang terlelap di depanku.
“Kata Dokter cuma kecapekan. Insya Allah besok udah bisa pulang.”, jawab Ibu sambil tersenyum.
Aku sedikit merasakan kelegaan di hati. Berarti paling tidak aku bisa kembali ke tanah rantauanku besok pagi.
“Alhamdulillah. Berarti besok aku bisa balik ke asrama.”, ucapku dengan datar.
Lagi, Ibuku hanya tersenyum. Senyum yang buatku sedikit bertanya-tanya. Malam ini aku menginap di Rumah Sakit bersama Kakak dan Ibuku. Kini, aku dapat melihat Ayahku tertawa. Bahkan, sedikit bercerita sesuatu padaku. Aku hanya miris. Merasakan keharuan atas apa yang kini terjadi pada Ayahku. Dan saat aku berada dalam henignya malam, tak kurasakan bahwa pipi ini basah bersama basahnya mukena yang kukenakan. Aku bersimpuh di hadap-Nya. Memuji asma-Nya dan meminta agar Ayahku selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin. Pagi tiba. Tak terasa semalam aku tertidur di atas sajadahku dan masih berbalut mukena. Kulirik jam tanganku. Pukul 4 pagi. Aku bergegas mandi dan sholat Shubuh. Tak lupa aku mendoakan untuk kesehatan keluargaku. Beberapa waktu kemudian, aku bersiap berangkat, kembali ke asrama. Aku akan diantar oleh Om Hanif, adik ipar Ayahku. Beliau telah siap. Aku berangkat setelah berpamitan pada Ayah dan Ibuku. Aku berjalan di belakang Om Hanif menuju tempat parkir. Kami memasuki mobil. Tak berapa lama, mobil telah meninggalkan pelataran parkir Rumah Sakit.
“Berarti kemarin kamu ijin, De??”, tanya Om Hanif yang tetap fokus pada kemudinya.
“Ya.”, jawabku singkat. Aku merasa aneh pagi ini.
“Kamu yang serius belajar di sana. Nggak usah mikir macem-macem. Pikiranmu itu di sana. Yang di rumah, insya Allah nggak apa-apa. Kamu kan pinter, De, jangan sampai ngecewain Bapak Ibu. Buat mereka bangga. Bentar lagi kenaikan kelas kan?? Yang rajin belajar yaa…”, ucap Om Hanif panjang lebar.
Ya, aku tak akan mau buat orang tuaku kecewa. Dan aku juga tak mau buat Om Hanif kecewa. Beliaulah yang menanggung semua kebutuhanku selama di Pesantren, mulai biaya sekolah, biaya hidup, dan lain sebagainya. Beliaulah ‘Pahlawan Keduaku’ setelah Ayah. Tak terasa, Toyota Vios milik Om Hanif memasuki pelataran Pondok Pesantren. Aku turun dan langsung berpamitan pada Om Hanif.
“Om langsung pulang ya. Harus cepet-cepet, ada perlu. Assalamu’alaykum.”, ucap Om Hanif sambil menutup kaca jendela mobil, dan segera memutar arah mobilnya.
Aku melihat mobil itu menghilang di tikungan, kemudian aku berjalan menuju asrama putri. Ada seseorang yang tampaknya memperhatikanku. Seorang laki-laki, seangkatan denganku. Tapi aku tak peduli dengan tatapannya. Aku berlalu tanpa melihat ke arahnya. Ia mendengus pelan. Bawalah pergi cintaku Ajak kemana engkau mau Jadikan temanmu… temanmu paling kau cinta Di sini ku pun begitu Mencintaimu di hidupku Di dalam hatiku…sampai waktu yang pertemukan kita nanti….. Lagu Bawalah Cintaku milik Afgan Syahreza, aku lantunkan. Serasa ada yang merasuk dalam hati. Entah. Hal itu terkadang aku rasakan. Wajar, usiaku hampir 17 tahun. Seseorang telah mengusik keheningan dan memecah lamunanku. Tapi, lupakan. Fokus pada studiku. Aku bersiap berangkat ke sekolah yang letaknya tak jauh dari asrama. Aku berjalan menikmati indahnya suasana di sekitarku. Aku merasakan kelegaanku.
“Ade Irma. Ade Irma, ke sini sebentar. Saya ada perlu sama kamu.”, ucap Ustadz Didi, pengampu pelajaran Matematika di Madrasah Aliyah.
“Ya.”, jawabku sambil berlari kecil memasuki kantor.
Aku mendekati Ustadz Didi, dan menunjuk sebuah kursi agar aku duduk di situ.
“Kamu darimana? Eh, maksud saya, kamu kemarin di asrama atau pulang?”, tanya beliau dengan tatapan selidik yang konyol.
Aku ingin tertawa melihatnya. Haha…
“Kemarin saya pulang. Nengok Bapak di Rumah Sakit.”, jawabku sambil tersenyum.
Beliau terdiam sejenak, “Ja.. Jangan bohong kamu!”,ucapnya dengan gagap nada tinggi.
Aku makin bingung. “Insya Allah, saya jawab dengan sejujurnya, Ustadz.”, jawabku tenang.
Ustadz Didi mengeryitkan dahinya, tampak bingung. Kini beliau menggaruk kepalanya yang, aku yakin, tidak gatal sama sekali.
“Saya jadi bingung. Tadi ada anak yang melaporkan sesuatu pada saya tentang kamu, tapi kamu tadi malam tidak di asrama. Aduh…”, ucapnya sambil geleng-geleng.
”Hah?? Melaporkanku?? Aku diam, Melaporkan apa, Ustadz??”, tanyaku penasaran dengan suasana hati makin tidak karuan.
Ustadz Didi ikut terdiam dan tiba-tiba bel berbunyi tanda jam masuk dan mulai pelajaran.
“Yah, sudah masuk. Saya nggak bisa jelaskan sekarang. Nanti saya bahas lagi, insya Allah. Sekarang kita masuk kelas dulu. Dan tolong bawakan LKS yang di atas meja sana.”, ucapnya sambil menenteng buku-bukunya dan menunjuk meja di sudut ruangan sana.
“Baik, Ustadz.”, jawabku dan segera berjalan mengambil LKS di atas meja sana.
Aku penasaran. Aku berjalan menuju kelas. Aku makin penasaran, heran dan aneh. Semua mata tertuju padaku. Semua terlihat mencibirku.
“Sok alim. Tapi nyatanya… Nggak banget deh!”, ucap seorang perempuan, adik kelasku di kelas XI.
Aku menatapnya dengan perasaan aneh, bingung dan sebagainya. Ada apa sebenarnya?? Apa kabar terakhir tentangku di sini?? Aku lalui pelajaran pertama dan kedua dengan buyarnya konsentrasiku. Benar-benar hilang fokusku. Apalagi setelah mendengar cerita dari Ustadz Didi barusan. Aku benar-benar tak tahu harus bagaimana. Seseorang telah mengatakan kabar palsu tentangku. Aku dituduh pergi dengan seorang lelaki tadi malam. Astaghfirullahal ‘adhiim. Aku hanya miris. Tangisku tak bisa kubendung.
“Udah lah, De. Aku tahu kamu nggak kayak gitu.”, ucap Diyah.
“Iya, De. Paling cuma kerjaan orang yang nggak suka sama kamu.”, ucap Mba Nia menimpali.
“Iya. Kan kemarin aku yang nyuruh kamu pulang.”, ucap Ayu.
Aku hanya bisa menangis. “Tega banget itu orang sama aku. Nggak tahu ya, kalau aku anak pahlawan?? Huhu…”, ucapku konyol sambil terus menangis.
Serentak teman-temanku tertawa. “Mba Ade loh! Sempet aja ngebanyol.”, kata Tiwi setengah tertawa.
“Udah lah, aku mau ke kelas aja.”, ucapku sambil menyeka airmata dan berjalan keluar kelas.
“Beneran??? Nggak malu kalau dilihat sama itu…….”, ucap Tiwi meledek.
Aku menoleh, memasang wajah bingung. “Sama siapa??”, tanyaku sambil berpikir.
”Sama itu tuh…. Sama yang kemarin dapet juara I. Haha….”, jawab Mba Nia dengan tawanya yang renyah.
“Iihh… ngayal banget! Nggak muluk-muluk deh! Nggak berharap juga. Tapi, kalau jodoh, aku nggak nolak. Hehe…”, ucapku terkekeh sambil berlari menjauhi mereka.
Teringat padanya. Mungkinkah aku jatuh cinta??? Atau hanya kagum padanya. “Please, De. Sinau sih ngapa!!!,”, ucapku dalam hati.
*****
Tiga hari kemudian. Padahal kemarin itu aku, bukan Ade. Kepentok udah ketahuan, aku kambing hitamin aja dia.
"Makanya nggak usak sok alim. Rasain sekarang dia dibenci sama semua orang. Hahahaha…”, ucap seorang perempuan diiringi dengan tawa teman-temannya.
Merasa sangat puas tampaknya. Tidak sengaja aku mendengarnya dari balik pintu kelas. Aku memasuki ruangan yang mereka tempati.
“Oh, jadi kamu toh. Dasar. Maunya apa kamu?? Pake segala laporin hal nggak penting kaya gitu. Kamu kalau iri sama aku nggak usah gitu caranya, Neng. Bagus apa??”, cerocosku tanpa pakai koma, apalagi titik.
“Kamu denger ya, De?”, tanyanya kebingungan.
Gelagapan. “Kalau aku nggak denger, aku nggak bakal bilang kaya gitu, Winda. Karepmu apa jane?? Aduh, keceplosan pake jawa. Maumu apa sebenernya?? Mau bikin namaku jelek di mata semua orang??? Selamat ya, kamu berhasil. Tapi aku bisa ngelakuin lebih dari itu. Ya nggak, Wi?? Ya nggak, Ay??”, ucapku dengan nada tinggi, tapi tak sampai tujuh oktaf, terlalu tinggi (ntar dikira lagi seriosa).
“Betul, betul, betul.”,jawab Tiwi dan Ayu. Winda tampak takut. Aku bisa melihat dari rautnya.
“Coba aja kalau bisa.”, tantangnya.
“Okeh. Emangnya aku takut sama kamu?? Cihh… orang kaya kamu mah tak tiup aja langsung mabur. Werrr… haha….”, kataku penuh percaya diri, lebih tepatnya angkuh.
Winda dan dua temannya berlalu dari tempat itu.
“Huuu…. Anak pahlawan dilawan, aku tembak pake senjata klenger loh!,” ucapku setengah teriak agar Winda mendengarnya. Tiwi dan Ayu tertawa dengan kerasnya.
“Okeh. Besok kalian temenin aku ke Ustadz Didi. Aku mau jelasin semuanya. Kalian jadi saksi mata buat kasus ini.”, ucapku layaknya detektif.
“Siap.”, jawab Tiwi dan Ayu bersamaan. Keesokan paginya.
“Jadi begitu ceritanya. Berarti sebenarnya yang tolol dia sendiri ya?? Sama aja kaya lapor tentang apa yang dia lakukan malam itu. Walah, bocah.”, ucap Ustadz Didi setelah mendengar apa yang aku ceritakan.
“Haha… katanya udah kepentok ketauhan sama Ustadz Sohib di depan gerbang. Jadinya saya yang jadi korban.”, jawabku dengan sedikit sinis.
Mengingat hal itu sangat membuatku geram. Gemas. Rasanya ingin menampar. “Ya, sudah. Kasus ini akan saya ajukan ke tingkat yang lebih tinggi supaya nanti bisa diselidiki lebih lanjut mengenai kebenarannya. Yang benar akan menang, insya Allah.”, ucapnya dengan nada yang bijaksana.
“Numben, biasanya agak gagap.”, kataku dalam hati.
Aku, Tiwi dan Ayu hanya tertawa kecil,
“Baik, Ustadz. Kami permisi dulu. Assalamu’alaykum.”, ucap Tiwi.
“Wa’alaykumussalam.”, jawab Ustadz Didi.
Kami beranjak dari tempat itu. Aku dan Ayu berjalan ke arah barat, menuju kelas kami, dan Tiwi berjalan ke kelasnya di sebelah timur. Sepanjang jalan aku dan Ayu bercakap-cakap tentang hal yang baru terjadi di kantor.
“Kok, numben Ustadz Didi nggak gagap ya?? Biasanya gagape poll! Ntu orang aslinya gagap apa nggak ya? Haha…”, ucapku ngelantur.
Ayu hanya senyum, menatap ke depan seolah menerawang sesuatu. Kemudian ia tertunduk bagai orang yang sedang menahan malu. Aku menoleh ke arahnya, bingung.
“Kamu denger nggak aku ngomong apa, Ay??”, tanyaku dengan datar.
Merasa diabaikan olehnya, aku sedikit muram.
“Eh. Hmm.. anu.. denger kok! Tapi kurang jelas. Bisa diulang?”, jawabnya serasa tanpa dosa.
Alamak. “Behh. Ogah ngulang! Nggak menayangkan siaran ulang!”, ucapku ketus sambil berjalan mendahuluinya.
Kini aku meninggalkannya di belakang.
“De… ‘Afwan. Tadi aku bener-bener lagi nggak konsen. Yah, mutung.”, ucap Ayu setengah bereriak.
Aku terus berjalan. Tanpa sengaja aku menabrak seseorang bertubuh jangkung. Aku terjatuh dan terpental beberapa sentimeter ke belakang. Aku mengaduh kesakitan. Kemudian aku mendongak,
“Kamu?”, ucapku takjub sembari menelan ludah.
Oh, tidak! Dia adalah virus yang selama ini mengganggu lamunanku.
“Kenapa? Kamu oke-oke aja kan? Nggak ada yang cedera kan?”, tanyanya dengan wajah kekhawatiran.
Aku melongo. Terpesona, mungkin.
“Hei. Hellow…”, katanya lagi sambil melambaikan tangannya di depan wajahku.
“Heh! Aku nggak apa-apa. Makasih udah bikin aku jatuh!”, ucapku ketus sembari bangkit dan berlalu meniggalkannya.
“Ketus amat. Hmm… tapi manis juga.”, ucap Diandar, orang yang menabrakku tadi, sambil tersenyum dan berjalan berlawanan arah denganku.
“Nightmare! Lupain! Lupain orang nggak penting itu! Lupain lupain!”, omelku yang kini mengundang perhatian teman-teman di kelasku.
“Apa sih, De?”, tanya Diyah yang tak lepas memandang LKS dihadapannya.
“Habis ditabrak orang nggak penting! Sampai jatuh pula! Iihhh…”, ucapku sambil menenggelamkan wajahku di antara kedua tanganku di atas meja.
“Siapa? Diandar?”, tanya Diyah padaku.
Aku terperangah, terkejut.
“Kok tahu?”, ucapku bingung. Diyah menoleh dan hanya tersenyum.
“Tadi malem kamu ngigau panggil-panggil Diandar.”, ucapnya santai.
Hah?? Aku tak percaya. “Apa iya? Jangan bohong kamu!”, ucapku dengan ekspresi tidak terima. Diyah mengada-ada pastinya.
“Wallahi.”, jawabnya singkat. Aku terdiam.
Mendengar kata itu aku tak bisa memungkiri bahkan mengelak. Diyah sudah bersungguh-sungguh atas nama Allah. Aku masih terdiam.
“Udah, belajar aja. Nanti ada ulangan Biologi loh!”, ucap Diyah.
Kacau! Aku baru ingat kalau nanti ada ulangan. Aku segera mengambil buku dan membukanya. Belajar Biologi. Satu minggu kemudian. Hasil ulangan Biologi diumumkan. Kali ini aku mendapat nilai tertinggi. Aku bahagia. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kelas. Semua mata tertuju pada sosok di luar sana. Ustadz Amir. Beliau masuk dan berbisik pada Ustadzah Ilma, pengampu Biologi di Madrasah Aliyah.
“Oh, iya. Silakan.”, ucap Ustadzah seolah memberi persetujuan.
“Ade Irma, ikut saya sebentar. Terimakasih, Ustadzah.”, ucap Ustadz Amir sambil berjalan keluar.
Aku bangkit dan mengikuti beliau keluar. Terheran-heran. Namun, aku tetap tenang mengikuti langkahnya. Aku sampai di kantor. Aku duduk di kursi coklat kayu di samping meja kecil di kantor itu.
“Ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kasus kamu dengan anak bernama Winda itu sudah selesai. Tadi malam dia datang ke rumah Ustadz Didi dan mengakui perbuatannya. Madrasah mengambil keputusan untuk mengembalikannya pada kedua orang tuanya….”, jelas Ustadz Amir.
“Ngikk? Drop Out maksudnya? Waduh..”, tanyaku dengan mata terbelalak.
“Iya, begitu kurang lebihnya. Dan kedua.. saya nggak mau basa-basi. Tadi kerabat kamu menghubungi kami, kamu disuruh pulang. Ada perlu di sana. Saya sarankan kamu pulang sekarang.”, ucapnya dengan nada ragu. Aku heran.
“Kenapa aku suruh pulang lagi?”, tanyaku dalam hati.
“Baiklah, Ustadz. Nanti saya ijin ke Wali Kamar.”, jawabku.
“Nggak perlu. Kami sudah ijinkan kamu ke Bidang Asrama.”, ucap Ustadz Amir,
“Kamu langsung pulang saja.”, lanjutnya. Aku keluar dari kantor setelah berpamitan.
Aku merasakan lemas yang luar biasa. Entahlah. Ada yang kurasa aneh dari perkataan Ustadz Amir tadi, seperti menyembunyikan sesuatu. *****
Aku tiba di rumahku. Sangat berbeda begitu aku memasuki jalan setapak menuju rumahku. Sangat ramai. Banyak sepeda motor berlalu lalang, keluar masuk halaman rumahku. Dan yang membuatku terkejut, bendera putih melambai-lambai di dekat pohon jambu di depan rumahku. Aku berlari sekencangnya menembus kerumunan orang-orang. Aku serasa hilang arah. Tiba aku di depan pintu rumah. Kulihat sesosok tubuh berbalut kafan putih kedua kalinya setelah wafatnya Kakekku dua bulan lalu. Kudekati sosok yang terbaring itu. Wajahnya pucat. Hidungnya tersumpal kapas. Aku mulai merasa airmata meleleh di pipiku.
“Bapaaaaakkkkk…….”, aku berteriak dan menangis sekerasnya.
Duniaku runtuh Jiwaku rapuh Ragaku meringkuk lesu Yaa Rabbiy.. Kaulah Sang Penggenggam Jiwa Lindungilah nyawa yang Kau hembuskan Lindungilah pula tiap nyawa yang Kau ambil kembali… Lindungilah Ayahku… Hatiku bersyair begitu. Memohon dan meminta perlindungan untuk Ayahku. Pandanganku buram. Remang-remang. Gelap. Aku mulai mencoba membuka mataku. Pening yang aku rasakan buatku enggan untuk bangkit.
“Pusing, De??”, tanya seseorang di sampingku, Kakakku.
Aku hanya mengangguk lemah sambil terus meringis kesakitan. Benar-benar pening.
“Kamu istirahat dulu. Mba tinggal bentar ya.”,ucap Kakakku sembari bangkit dan berlalu.
“Bapak dimana?”, tanyaku layaknya bocah kecil.
“Barusan dibawa ke pemakaman.”, jawab Kakakku singkat dan melanjutkan langkahnya keluar.
Aku lemas. Suasana duka masih aku rasakan. Seolah meruntuhkan dinding semangatku yang telah kubuat dari beberapa minggu yang lalu. Maklum, minggu depan akan berlangsung Ulangan Umum Kenaikan Kelas. Terkadang aku mengeluh. Aku kehilangan Ayahku saat aku ingin menunjukkan sesuatu yang hebat pada beliau. Ya, prestasiku saat kenaikan kelas XII, itulah yang ingin aku tunjukkan agar buat beliau bangga. Namun, harapan itu kandas. Aku harus segera kembali ke asrama. Aku tak mungkin berlama-lama di rumah. Dengan sedikit berat hati, aku berangkat.
“Hati-hati ya, Nduk. Sinau sing rajin. Ojo mikir macem-macem. Gawe bapak seneng neng kono.”, ucap Ibuku sambil menangis memelukku.
“Iya, Bu. Doain nilaiku apik.”, jawabku sembari melepas pelukan Ibuku.
“Assalamu’alaykum.”, ucapku lagi sambil berjalan keluar rumah.
“Wa’alaykumussalam.”, jawab Ibu dan Kakakku bersamaan.
Aku berangkat dengan bis umum. Sepanjang perjalanan, aku lebih banyak diam. Memandang keluar melalui jendela bis. Terbayang siluet memori bersama Ayahku. Banyak sekali kenangan indah bersama beliau. Terlalu jauh aku mengkhayal, hingga tak terasa seseorang sedang mengamatiku.
“Permisi.”, ucapnya. Aku sedikit terlonjak kaget.
“Kamu? Kok bisa di sini??”, tanyaku padanya.
Orang itu lagi! “Ya, niatnya aku mau ke rumah kamu. Mewakili kelas untuk ta’ziyah. Malah kamu udah mau balik ke Pondok. Ya udah, akhirnya aku ngikutin kamu.”, jelasnya sambil tersenyum lebar. Manis.
“Oo… tapi kenapa harus kamu?”, tanyaku heran.
Dia justru tertawa lebar mendengar pertanyaanku. Orang aneh, pikirku.
“Aku kan ketua kelas.”, jawabnya singkat.
Dengan sedikit malu, aku mengalihkan pandanganku keluar jendela. Setelah itu, kami terdiam sampai ke tempat tujuan.
*****
Sebulan kemudian. Hari ini adalah pembagian hasil Ulangan Umum Kenaikan Kelas. Aku pasrah.
“Situ lah, nilaiku mau berapa. Kemarin aku ngerjainnya nggak niat. Nggak semangat. Ketambahan ada virus. Bah, aku ngerasa bego banget gara-gara itu orang!”, omelku didepan cermin, bersiap-siap akan berangkat ke sekolah, mengambil buku Raport.
“Emang gara-gara siapa? Hayooo….”, ledek Ana, teman sekamarku. “Oh.. anu.. itu lah. Orang nggak penting.”, jawabku gelagapan. Bahaya kalau dia tahu. Aku berjalan menuju kelas untuk mengambil Raport. Tiba-tiba ada teman-temanku, yang berjalan dari arah kelas, menyalami sambil tersenyum padaku.
“Selamat, De. Dapet ranking I nih! Semangat terus ya!”, ucap Ima. Aku bingung.
“Apa sih? Emang ranking I ya?”, tanyaku dengan nada blo’on.
Semua teman-temanku tertawa lepas melihat kebodohanku. Aku yang tidak percaya, langsung berlari kencang menuju kelas. Tiba di depan kelas, aku berhenti sejenak. Kemudian, aku berjalan perlahan memasuki kelas.
“Ade Irma. Silakan, ini buku Raportmu. Selamat, terus tingkatkan prestasimu.”, ucap Ustadzah Zakiyah, wali kelasku.
Aku makin tidak percaya. Aku buka lembar-lembar Buku Hijau itu. Tertulis angka ‘I’ di kolom peringkat.
“Hah??? Aku… ranking I?? Ya syok! Haha……….”, ucapku sambil tertawa bahagia.
“Alhamdulilah… Bapak, aku ranking I. Semoga Bapak seneng tahu prestasiku di sana.”, ucapku dalam hati.
Aku berlari keluar kelas, menghampiri teman-temanku sambil melompat-lompat kegirangan. Teman-temanku hanya tertawa melihat tingkahku.
“Ani.”, panggil seseorang di belakangku.
Aku bersungut-sungut.
“Jangan panggil……….. kamu lagi???”, ucapku kaget.
Akupun melongo. Terpesona untuk kesekian kalinya. Senyumanmu buat aku deg-degan Tatapanmu buatku jadi deg-degan Diandar.
“Selamat ya… Jangan pernah menyerah hanya karena kamu kehilangan orang yang kamu sayangi. Bentar lagi kita kan kelas XII, harus makin rajin. Berjuang sama-sama yaa….”, katanya sambil tersenyum manis.
Lagi, aku melayang. Mungkinkah ada rasa???
“Iya. Makasih banyak, Andar.”, ucapku sedikit kikuk.
Diandar berlalu, namun menoleh dan tersenyum lagi.
“Kalau lulus, ngajar di sini aja. Kamu bakal ketemu sama aku.”, ucapnya lagi kemudian pergi dengan senyum manisnya.
Dan harus kusadari. Aku mengaguminya. Dan akupun harus menyadari, kehilangan seseorang yang aku sayangi tak semestinya membuatku terjatuh dan lemah. Walaupun seseorang itu takkan abadi, tapi aku yakin kegigihannya dalam menjalani hidupnya yang harus aku teladani.
“Bapak, semangatmu abadi dalam jiwaku. Aku akan buatmu bangga walau kau tak bisa melihatku dalam dunia nyata. Kau dalam keabadian di sisi-Nya.”, bisikku dalam hati.
Tuhan tolonglah Sampaikan sejuta sayangku untuknya Ku trus berjanji takkan khianati pintanya Ayah dengarlah Betapa sesungguhnya ku mencintaimu Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu Aku menatap Diandar yang kini berada di ujung jalan sana. Dia menoleh ke arahku, dan melambaikan tangannya padaku. Aku hanya tersenyum.
“Ciyeehhhh….. jadi dia orang yang nggak penting itu??”, tanya Ayu dengan nada meledek.
“Sekarang dia penting buat aku.”, jawabku, namun hanya dalam hati.
Itu sudah, tahun depan aku akan menghadapi sesuatu yang lebih istimewa, Ujian Nasional. Aku harus lebih semangat lagi.
“Bapak, doakan aku.”, bisikku lagi.
Semua belum berakhir. Masih perlu ada perjuangan untuk meraih yang aku inginkan.
*****
(Karya Kusmaningsih)
Share this article with your friends

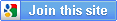












Posting Komentar
Jangan berkunjung tanpa meninggalkan jejak.
- No Spam - No Phising - No Live Link
Salam Blogger Indonesia, Silakan Tinggalkan Pesan Agan disini... !!!